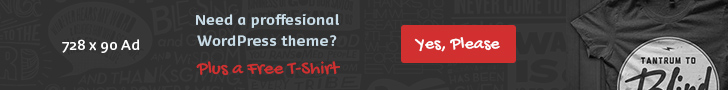Di tengah gemuruh ekonomi dan gempita politik nasional, ada satu istilah yang selalu hadir dalam percakapan sunyi. “9 Naga.” Ia bukan lembaga resmi, bukan organisasi bisnis, apalagi entitas hukum. Tapi entah mengapa, namanya terus hidup dalam berbagai teori konspirasi, diskusi warung kopi, bahkan forum akademik. Siapa mereka? Dan yang lebih penting: mengapa kita terus membicarakan mereka?
Istilah “9 Naga” mengacu pada sekelompok kecil konglomerat Tionghoa-Indonesia yang katanya memiliki pengaruh besar dalam perekonomian nasional. Nama-nama seperti Hartono, Salim, Riady, Tahir, hingga Tommy Winata sering kita dengar dalam kelompok ini. Mereka mengendalikan sektor strategis: perbankan, makanan, properti, transportasi, hingga media. Kekayaan mereka berlapis-lapis. Jaringan mereka lintas generasi dan rezim. Tapi, apakah mereka benar-benar beroperasi sebagai satu entitas? Atau ini hanya konstruksi sosial penuh kecurigaan?
Antara Fakta dan Imajinasi
Sulit dibantah bahwa para taipan ini memiliki posisi dominan dalam lanskap ekonomi Indonesia. Namun, menyebut mereka sebagai “9 Naga” seolah-olah mereka duduk dalam satu meja dan menyusun rencana bersama, jelas terlalu disederhanakan. Sebagian besar dari mereka bahkan bersaing satu sama lain, baik di sektor bisnis maupun dalam akses ke penguasa.
Namun yang menarik, istilah ini tetap hidup. Masyarakat membicarakan mereka seolah mereka makhluk tunggal, pengatur takdir ekonomi nasional. Ini menunjukkan bahwa “9 Naga” lebih dari sekadar sembilan individu. Mereka adalah simbol kecemasan kolektif terhadap struktur ekonomi yang dianggap tidak adil, dan terhadap oligarki yang sulit ditembus oleh rakyat biasa.
Konspirasi yang Mengisi Kekosongan
Ketika harga beras naik tanpa alasan jelas, ketika pengusaha kecil gulung tikar, ketika keputusan pemerintah terasa berat sebelah, masyarakat butuh penjelasan. Dalam ruang kosong itu, teori konspirasi tumbuh subur. “Pasti ulah 9 Naga,” kata sebagian orang. Padahal realitasnya seringkali jauh lebih kompleks dan tidak sesederhana itu.
Namun teori konspirasi, betapapun simplistik, punya satu kekuatan: ia memuaskan dahaga akan narasi. Narasi bahwa ada yang bertanggung jawab. Bahwa ketidakadilan bukan semata takdir, tapi ada tangan-tangan besar yang mengaturnya.
Kuasa yang Tak Terlihat
Salah satu daya tarik “9 Naga” adalah bagaimana mereka digambarkan: tidak tampil di panggung politik, tapi memengaruhi keputusan penting dari balik layar. Mereka jarang muncul di media, tidak mencalonkan diri, tapi mendanai partai. Mereka tak bicara soal kebijakan, tapi proyek-proyek mereka seringkali selaras dengan arah kebijakan negara.
Di sinilah letak paradoksnya. Dalam demokrasi yang ideal, kekuasaan seharusnya berasal dari legitimasi publik. Tapi dalam praktiknya, kekuasaan bisa bersumber dari modal, dan modal tidak perlu kampanye untuk menang.
Menyambut Naga-Naga Baru?
Menariknya, hari ini kita menyaksikan munculnya sosok-sosok baru yang seolah mengambil peran “naga generasi kedua.” Nama-nama seperti Aguan (Agung Sedayu Group), Jerry Ng (Bank Jago), hingga Prajogo Pangestu (Barito Group) mulai mencuat sebagai figur berpengaruh dalam proyek-proyek nasional—terutama Ibu Kota Nusantara (IKN). Mereka tidak selalu masuk daftar “9 Naga” klasik, tapi dalam praktiknya, kekuatan mereka sama—jika bukan lebih besar.
Apakah ini regenerasi naga? Atau sekadar perubahan bentuk dari kekuasaan lama?
Penutup: Yang Perlu Kita Waspadai
Apakah 9 Naga itu nyata? Mungkin. Tapi lebih penting dari pertanyaan itu adalah apa yang kita pelajari dari keberadaan (atau bayangan) mereka. Bahwa ekonomi Indonesia masih sangat terkonsentrasi. Bahwa akses terhadap modal dan kekuasaan tetap terbatas pada segelintir. Dan bahwa transparansi dalam hubungan antara bisnis dan kekuasaan masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Alih-alih terus menerus hidup dalam bayang-bayang mitos, kita perlu mendesak sistem yang lebih terbuka, adil, dan demokratis—di mana kekuasaan, dalam bentuk apa pun, tak bisa terus bersembunyi di balik tirai.